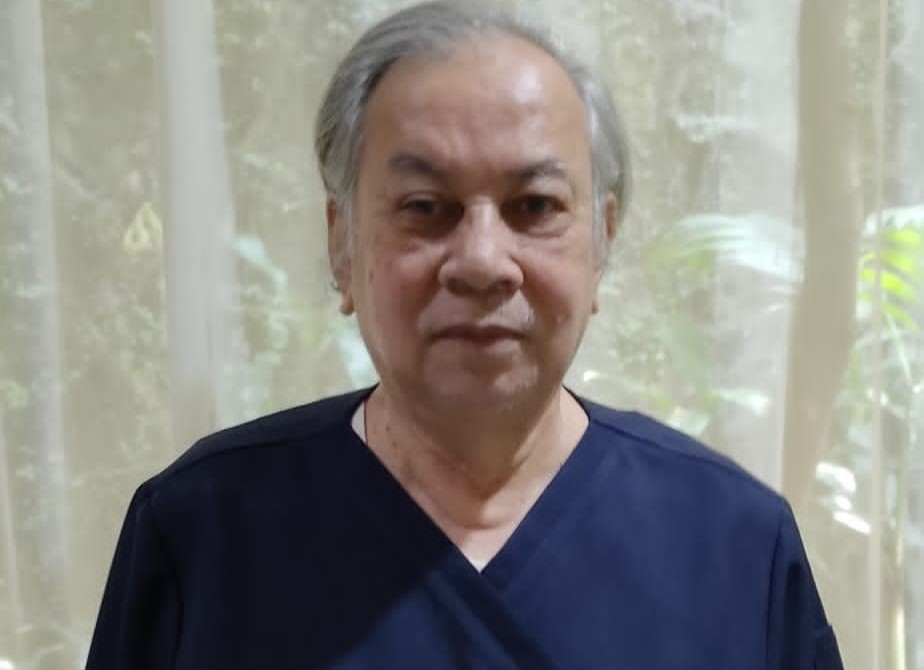
Oleh Suryono SIS, SpOG,
SIAPA yang tak kenal Kartini? Sosok pahlawan pembela kaum perempuan yang perjuangannya tidak hanya menyentuh persoalan yang kita pahami sebagai kesetaraan gender. Terlahir sebagai anak keluarga bangsawan, Kartini berupaya mendobrak hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan kaum perempuan di masanya terpinggirkan.
Perjuangannya agar perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan salah satunya ia wujudkan dengan mendirikan sekolah bagi anak perempuan. Namun sayang, Kartini wafat di usia yang terbilang muda, 25 tahun, tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Ia meninggal 4 hari setelah melahirkan putera tunggalnya.
Beberapa literatur menyebutkan Kartini meninggal disebabkan pre-eklamsia, suatu kondisi dari komplikasi kehamilan yang ditandai peningkatan tekanan darah tinggi serta gangguan kesehatan lainnya.
Perempuan Masih Terpuruk
Sudah 119 tahun berlalu sejak wafatnya Kartini, kondisi perempuan Indonesia masih saja terpuruk terutama dalam hal derajat kesehatan. Hal ini dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia.
Berdasarkan data SUPAS 2015, AKI di Indonesia mencapai 305/100.000 kelahiran hidup. Wafatnya Kartini mengingatkan kita bahwa kematian ibu merupakan persoalan serius yang sudah ada sejak jaman dahulu hingga saat ini.
Dalam surat Kartini pada Oktober 1901 yang ia tulis untuk sahabat penanya Estella Zeehandelaar, Kartini menceritakan setiap tahun ada sekitar 20 ribu perempuan meninggal saat melahirkan dan 30 ribu anak lahir meninggal karena pertolongan bagi perempuan bersalin yang kurang memadai.
Rendahnya capaian penurunan AKI di Indonesia menimbulkan rasa pesimis dari kalangan pemerhati kesehatan perempuan, Indonesia akan bisa mencapai target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar 183/100.000 kelahiran hidup pada 2024 dan target Sustainable Development Goals (SDGs) sebesar 70/100.000 kelahiran hidup yang menjadi komitmen global.
Berdasarkan penelitian Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) pada tahun 2016 – 2018, diketahui beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu antara lain: kualitas pelayanan kesehatan; sistem rujukan; implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); kebijakan pemerintah daerah; serta faktor budaya.
Masyarakat di beberapa daerah di Indonesia masih memegang prinsip perempuan tidak berhak menentukan proses persalinannya. Hal ini membuat banyak kasus perempuan melahirkan dalam kondisi darurat dan sulit ditolong.
Keluarga melarang ibu hamil dirujuk ke fasilitas medis yang masih memadai. Perempuan untuk melahirkan di rumah sakit saja harus menurut keputusan suami dan keluarga.
Konstruksi sosial yang dibangun dalam budaya patriarki dalam melihat perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan bagi perempuan. Budaya patriarki menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dalam tatanan keluarga serta komunitas.
Tidak Memiliki Hak atas Tubuh Sendiri
Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan sehingga perempuan tidak memiliki pilihan atas tubuh dan hidupnya termasuk dalam hal memutuskan kapan perempuan ingin hamil, bagaimana ia merawat kehamilannya, bagaimana ia bersalin, dan sebagainya. Seolah perempuan mahluk tidak berdaya yang tidak memiliki otonomi penuh atas tubuhnya sendiri.
Pada komunitas dengan budaya tertentu, anak laki-laki sering kali dianggap memiliki nilai lebih tinggi dibanding anak perempuan. Nilai-nilai ini diajarkan secara turun menurun dan terbentuk dari hasil sosialisasi baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah maupun interaksi dengan masyarakat. Hal ini turut mempengaruhi pola asuh dan pemenuhan kebutuhan anak seperti hak atas kesehatan dan pendidikannya.
Perempuan sering kali dinilai dari fungsi reproduksinya sebagai contoh nilai perempuan yang ideal adalah perempuan yang bisa melahirkan dan menyusui. Padahal proses kehamilan harus terjadi karena adanya laki-laki dan perempuan. Masih banyak perempuan di negeri ini yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatannya
Ketidaksetaraan gender turut mempengaruhi pola pikir kalangan profesi kesehatan. Praktisi kesehatan umumnya melihat persoalan kesehatan perempuan semata-mata menyangkut masalah klinis semata tanpa berupaya menggali isu non-klinis yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan perempuan. Mereka juga tidak melihat adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun berbeda hanya saat perempuan hamil dan melahirkan. Karena itu pendidikan bagi calon profesi kesehatan yang sedianya memberikan layanan kesehatan perempuan hendaknya tidak hanya menggunakan “kaca mata” medis klinis.
Reproduksi Perempuan Sebagai HAM
Penyelenggara pendidikan bagi profesi kesehatan juga perlu mengedukasi peserta didiknya agar memiliki kepekaan terhadap situasi sosial, gender dan menghargai hak reproduksi perempuan sebagai hak asasi manusia (HAN), sehingga pasca pendidikan, tenaga kesehatan peka terhadap relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, budaya, serta nilai-nilai dan isu sosial lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan perempuan tempat ia bertugas.
Para tenaga kesehatan juga diharapkan mampu memberikan pendidikan kesehatan untuk memberdayakan perempuan, sehingga setiap perempuan dapat menentukan pilihan atas tubuhnya termasuk dalam hal merencanakan kehamilan yang sehat, mempersiapkan persalinan yang aman serta menghindari risiko kehamilan tidak diinginkan. Kematian ibu dapat dicegah jika perempuan mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tanpa mengabaikan pentingnya pendidikan kesehatan perempuan yang komprehensif.*
Penulis adalah Dokter Spesialis Obstetri-Ginekologi dan Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP), Ketua POGI periode 2003 – 2009




