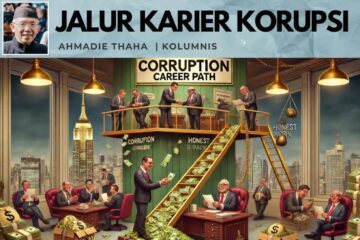Oleh Dhorifi Zumar
MEMASUKI musim pesta demokrasi rakyat, baik Pileg (Pemilihan Legislatif), Pilpres (Pemilihan Presiden) maupun Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2024, sikap umat Islam Indonesia umumnya terbelah menjadi dua. Pertama, mereka yang antusias menyambut perhelatan lima tahunan tersebut, dan kedua, mereka yang apatis bahkan antipati dengan pesta demokrasi tersebut.
Bagi yang antusias, mereka memaknai pesta kontestasi politik lima tahunan tersebut sebagai mekanisme yang sah, legal, dan demokratis untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan. Meskipun syariah Islam lebih mengutamakan mekanisme musyawarah (syura) ketimbang demokrasi dalam memilih seorang pemimpin, tapi demokrasi juga bukan sesuatu yang tabu dan haram dalam Islam.
Pandangan ini sejalan pendapat Yusuf al-Qardhawi (1926-2022), seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, dalam “Fatawa Mu’ashiwah” (1988) menegaskan bahwa esensi demokrasi berdekatan dengan roh syura Islamiah. Bahkan, secara dramatis dia menyebut demokrasi sebagai barang hilangnya umat Islam. (Hajriyanto Y. Thohari, Demosyurakrasi, hlm.189, dalam Muhammadiyah dan Orang-orang yang Bersahaja, 2021)
Syekh Muhammad al-Ghazali (1917-1996), seorang ulama, intelektual, dan aktivis dari Mesir, dalam buku “Miatu Sual ‘an al-Islam” pun mengatakan sistem demokrasi atau pemilihan (umum) tidak menjadi aib untuk ditiru umat Islam di negeri Muslim hanya karena bangsa asing telah terlebih dahulu mempraktikkannya.
Begitu pula cendekiawan Muslim Indonesia, Nurcholish Madjid (1939-2005) atau biasa dipanggil Cak Nur dalam “Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi” (1999) menyatakan, berkat prinsip syura yang begitu fundamental dalam Islam, penerimaan umat Islam akan demokrasi modern sangat alami.
Dr Hasan Ibrahim dkk, dalam karyanya “al-Nudhum al-Islamiyah” juga menulis bahwa gagasan tentang demokrasi sudah ada pada masyarakat Arab pra-Islam. Dalam masyarakat itu terdapat suatu majelis tetua kabilah bernama majelis syuyukh al-qabilah, dimana di dalam majelis inilah dimusyawarahkan dan diputuskan urusan-urusan penting, seperti deklarasi perang, penetapan perdamaian, ataupun perkara-perkara yang dapat memacu gerak sistem kesukuan.
Kemudian setelah Islam datang, prinsip syura ini diambil alih tapi diberi dasar dan orientasi baru. Bila pada masa pra-Islam, konsep syura itu didasarkan pada ‘urf (adat istiadat) kesukuan, maka pada masa Islam fondasinya diganti dengan iman yang bernilai universal dan diarahkan untuk mewujudkan persaudaraan antarumat manusia. (Ahmad Syafii Maarif, Kedudukan Negara dalam Perspektif Doktrinal Islam, 1994)
Integral, Bukan Parsial
Dus berarti bagi kelompok pertama ini, Islam dan politik adalah dua hal yang integral, tidak parsial. Karena Islam adalah agama yang kaffah atau komprehensif, yang tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual (mahdhah) belaka, tetapi juga mengatur urusan masyarakat dan negara. Artinya, Islam itu ad-din (agama) dan ad-daulah (negara), sebagaimana ditegaskan oleh Dr Muhammad Yusuf Musa dalam “Nidham al-Hukmi fi al-Islam” dan pendapat ini diamini juga oleh Prof Amien Rais.
Dari sini tak disangkal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik urusan keluarga, kemasyarakatan, pemerintahan maupun hubungan internasional. Salah satu bukti sejarah perpolitikan dalam Islam adalah momen pengangkatan seorang khalifah (kepala negara), selepas wafatnya Rasulullah SAW.
Rasulullah pun pernah bersabda, “Barangsiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin).”
Di mata mereka, politik bukan sesuatu yang buruk, kotor dan jahat. Politik adalah entitas yang netral, tergantung siapa yang menggunakannya. Bagai sebilah pisau, barang itu bisa bermanfaat jika berada di tangan orang baik dan bijak, sebaliknya bisa berbahaya jika berada di tangan orang yang jahat. Bagi kelompok pertama, dengan politik, keadilan bisa diwujudkan, kesejahteraan masyarakat pun akan bisa didapatkan. Artinya politik menjadi sarana atau wasilah untuk mencapai kebahagiaan hidup.
Hal ini sesuai dengan filsafat politiknya Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Kindi (805-873 M), filsuf Muslim awal yang masyhur dengan sebutan al-Kindi. Bagi Al-Kindi, hakikat politik adalah menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain. Dalam konteks negara, bisa diartikan sebagai usaha pemimpin dalam menghadirkan kebahagiaan untuk rakyatnya. Kebahagiaan rakyat bisa disamakan dengan kesejahteraan dan rasa aman.
Dengan demikian, dalam filsafat politik al-Kindi, pemimpin mestinya menghadirkan kebahagiaan, bukan saling rebut kekuasaan dan jabatan serta saling menjatuhkan satu sama lainya. Sebab, tujuan akhir politik pada hakikatnya adalah menyejahterakan dan menenteramkan kehidupan rakyatnya.
Begitu pula Abū Nashr Muḥammad Al-Farabi (870-950 M) mengemukakan teori al-Madīnah al-Fāḍilah yang mengusung konsep kenegaraan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul dan khalifah sekaligus. Dalam teori politiknya, Al-Farabi menekankan bahwa tujuan utama bernegara adalah tercapainya kebahagiaan bagi warga negara. Dengan teori organik, Al-Farabi menyatakan bahwa pemerintahan dalam negara itu seperti halnya sistem organisme tubuh manusia, di mana setiap unsur yang ada saling memperkuat untuk mencapai satu tujuan.
Negara ideal bagi Al-Farabi adalah negara yang bertujuan untuk kesejahteraan warganya, dan yang menjadi pimpinan utama adalah seorang filsuf yang memiliki sifat-sifat Nabi, berpengetahuan luas, dan dapat mengadakan hubungan dengan al ‘aql al fa’al melalui akal mustafad.
Apatisme yang Membuncah
Sebaliknya bagi mereka yang apatis terhadap politik memandang bahwa politik itu buruk, kotor, jahat, dan memecah belah. Pandangan mereka itu didasarkan pada fakta munculnya keterbelahan (polarisasi) masyarakat pasca kontestasi Pilpres tahun 2014 dan 2019 yang lalu. Dalam sejarah republik ini, bisa dibilang pada periode inilah untuk pertama kali muncul ‘konflik politik’ yang sangat massif dan dikhawatirkan akan menjurus pada potensi perpecahan bangsa, akibat endorsement pada masing-masing Capres (Calon Presiden) yang kebablasan atau berlebihan.
Keterbelahan itu mungkin saja ada andil besar dari medsos (media sosial), dimana setiap orang menjadi begitu mudah menumpahkan uneg-uneg dan opini atau komentarnya lewat medsos. Sehingga pihak-pihak yang kurang berkenan atas opini atau komentar yang dilontarkan lawan politiknya itu dengan serta merta memberikan komentar balik disertai dengan ejekan, hujatan dan cacian. Situasi saling lempar ejekan, hujatan dan cacian di medsos itu makin diperparah dengan tampilnya Buzzer, yaitu pihak yang menjadi pendengung atau pembela bagi kubu salah satu Capres.
Kehadiran para Buzzer politik malah bikin situsi perpolitikan nasional makin runyam dan kacau, sebab dari situ kemudian muncul istilah Cebonk, Kampret, Jingrab (Anjing Kurab) maupun Kadrun (Kadal Gurun). Istilah-istilah yang merupakan stigmatisasi pada masing-masing pendukung Capres. Dari istilah-istilah yang kurang simpati dan berbau binatang itu, maka keterbelahan pendukung capres makin melebar dan panjang. Masing-masing kubu akan mendidih emosinya atau meledak amarahnya jika terstigma dengan istilah-istilah kotor tersebut.
Alhasil, mereka langsung menjudge bahwa politik itu kotor, tidak beradab dan memecah belah. Kemudian tahap berikutnya mereka menjadi apatis dan antipati terhadap isu-isu politik. Jika ada salah seorang menshare postingan berbau politik di grup medsos mereka langsung reaktif dan menunjukkan ketidaksukaannya.
Tak hanya itu, apatisme mereka terhadap politik semakin membuncah dengan adanya perilaku politik belah bambu yang dilakukan oleh penguasa (rezim) saat ini terhadap kekuatan politik, utamanya partai politik. Sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno di era Demokrasi Terpimpin pada akhir 1950-an hingga 1960-an. Alhasil kekuatan parpol kemudian terpecah menjadi beberapa kekuatan baru, misalnya dari PAN muncul Partai Ummat, dari PKS muncul Partai Gelora, dari Partai Demokrat muncul Partai Kedaulatan Nusantara (PKN).
Selain itu, perilaku koruptif yang dipertontonkan oleh para anggota legislatif dan juga eksekutif maupun yudikatif yang seolah kian massif dan vulgar belakangan ini, makin menjadikan kelompok yang apatis terhadap politik menemukan pembenaran bahwa politik itu memang kotor, koruptif, dan tak tahu malu. Padahal apatisme dan kebencian terhadap politik itu bisa melahirkan sikap buta politik.
Penyair Jerman Bertolt Brecht mengatakan, “Orang yang buta politik itu tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, juga lahirnya pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional, semuanya tergantung pada keputusan politik.”
Lebih dari itu, sikap buta politik akan menjadi malapetaka bagi umat Islam Indonesia yang merupakan populasi terbesar di negeri ini. Necmettin Erbakan, guru Erdogan yang pernah menjadi Perdana Menteri Turki pada periode 1996-1997 pernah mengingatkan, “Muslim yang tidak pedulikan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak pedulikan orang Islam.”
Karena itu, umat Islam harus mengerti dan tidak boleh buta tentang perpolitikan nasional. Kalau umat Islam tidak berpolitik, maka yang berkuasa mereka yang berseberangan akidah dengan Islam, tidak mampu membantu, membela serta memperjuangkan aspirasi umat Islam di kancah politik nasional.*
Penulis adalah kontributor Majalah Siber Indonesia J5NEWSROOM.COM, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalibaru Kota Depok, dan anggota Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah.