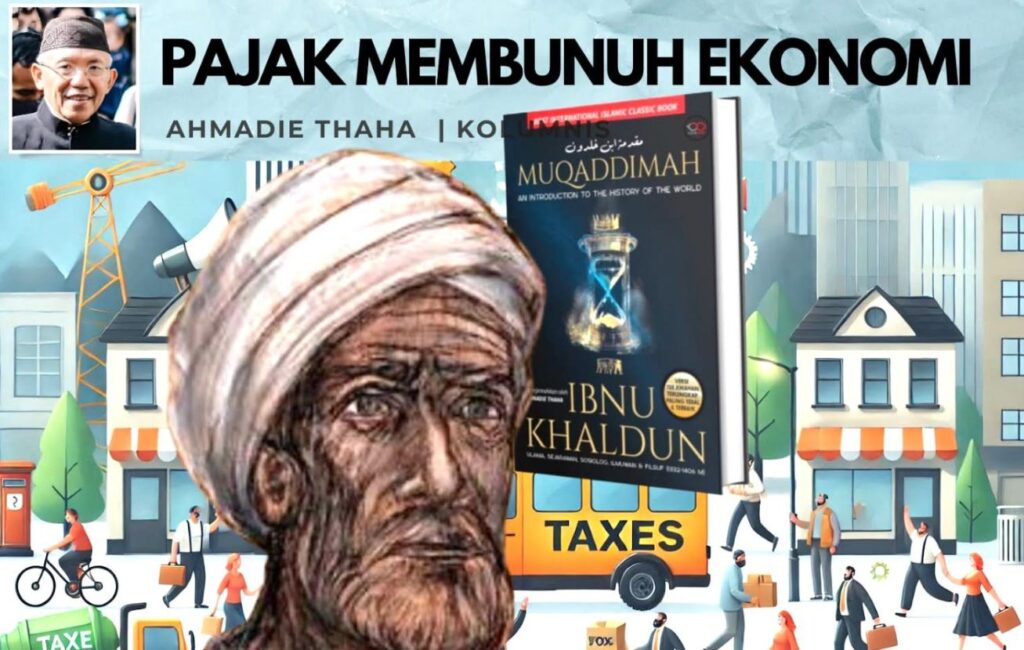
Catatan Cak AT Ahmadie Thaha
BAYANGKAN kita hidup di negeri Maghribi abad ke-14, di tengah peradaban Islam yang sedang bergelora. Sebuah negeri yang kini dikenal dengan Maroko di Afrika Utara, yang dibangun oleh pedagang, petani, dan cendekiawan, namun tetap membutuhkan pemasukan untuk mengurus birokrasi dan menjaga stabilitas politik.
Ibnu Khaldun, sang bapak sosiologi ekonomi, lahir dan besar di sana. Ia menyaksikan langsung bagaimana para penguasa lama-kelamaan memungut pajak secara berlebihan demi membiayai gaya hidup borjuis mereka yang bergelimang kemewahan. Ini berimbas ekonomi anjlok. Tidak heran jika ia berkata, “Pajak tinggi akan membunuh ekonomi.”
Ibnu Khaldun percaya pada sebuah siklus ekonomi, selain pada teori siklus negara: ketika pajak rendah, produktivitas dan perdagangan meningkat, sehingga pendapatan negara naik. Sebaliknya, pajak tinggi akan mematikan usaha rakyat, membuat ekonomi stagnan, dan pada akhirnya malah mengurangi pemasukan negara.
Dalam kitab Muqaddimah, karyanya yang monumental dan dipuji oleh para tokoh semisal Mark Zuckerberg, ia menulis bahwa penguasa yang bijak adalah mereka yang memungut pajak secara moderat, menciptakan keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kebutuhan negara. Pajak tetap ada, tapi tidak berlebihan.
Kita pindah ke Indonesia abad ke-21. Di negeri ini, pajak diatur seperti dalam permainan monopoli —banyak peraturan, tapi entah kenapa selalu kalah dalam mengejar ‘modal besar’. Sejak reformasi perpajakan 1998, rasio pajak terhadap PDB terus menurun, kini hanya sekitar 9%. Bandingkan dengan negara-negara maju seperti Jerman atau Prancis yang mencapai 40%. Namun, apakah itu berarti rakyat Indonesia hidup lebih makmur? Tidak juga.
Ibnu Khaldun akan mengelus dada jika melihat pengelolaan pajak di Indonesia. Pajak yang tidak efisien, akal-akalan biaya oleh korporasi besar, hingga korupsi para petugas pajak menjadi gambaran ironi di negeri ini. Belum lagi pajak pertambahan nilai (PPN) yang langsung menghantam daya beli masyarakat kecil. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, sistem ini bukan hanya tidak produktif, tapi juga destruktif. Ia juga memupuk sikap manipulatif.
Ibnu Khaldun mengusulkan alternatif yang menarik: berbasis bagi hasil. Di sektor pertanian, misalnya, penguasa di masanya lebih mengutamakan musyarakah (kemitraan), sebuah konsep ekonomi Islami, di mana hasil panen dibagi antara petani dan negara. Sistem ini mendukung produktivitas karena memberikan insentif langsung kepada rakyat.
Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang mirip, terutama dalam sektor minyak dan gas melalui skema bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC). Pada masa keemasannya, model ini berhasil mendongkrak pendapatan negara tanpa terlalu membebani rakyat. Namun, kini fokus berubah ke pajak-pajak tambahan yang justru membatasi ruang gerak investasi dan menggerus potensi pendapatan negara.
Pajak di Indonesia juga memiliki jejak kolonial yang pahit. Dari sistem landrente Raffles hingga kebijakan Belanda, pajak digunakan sebagai alat eksploitasi. Tidak heran jika sejarah mencatat pemberontakan besar seperti Perang Diponegoro (1825-1830) sebagai bentuk perlawanan terhadap pajak yang menindas. Sejarah ini seharusnya menjadi pelajaran penting: sistem perpajakan yang represif hanya akan melahirkan ketidakadilan dan perpecahan sosial.
Jika Ibnu Khaldun hidup di Indonesia hari ini, ia mungkin akan memberi konsultasi gratis pada negara, “Jangan mengejar pajak tinggi dari rakyat kecil. Kejar sumber daya alam kalian yang luar biasa.” Indonesia adalah eksportir batubara, sawit, dan nikel terbesar di dunia. Bukankah lebih masuk akal untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya ini melalui sistem bagi hasil, daripada terus membebani masyarakat dengan pajak?
Namun, ironinya, sistem pajak justru sering menjadi alat bagi para pengusaha besar untuk mengakali kewajiban mereka, “mendidik” mereka bersikap curang dan bohong. Dengan memperbesar biaya operasional secara manipulatif, laba kena pajak mereka menyusut, dan setoran ke negara pun minim. Sistem perpajakan seperti ini bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak efisien serta tidak mendidik.
Dalam pandangan Ibnu Khaldun, sistem ekonomi yang ideal adalah yang mendukung kesejahteraan rakyat sekaligus memastikan keberlanjutan negara. Indonesia perlu kembali ke prinsip ini. Alih-alih mengandalkan pajak yang cenderung eksploitatif, negara sebaiknya memperkuat sistem berbasis bagi hasil (musyarakah) terutama dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pajak boleh tetap ada, tetapi sebagai instrumen pendukung, bukan fondasi utama. Dengan begitu, Indonesia bisa menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, persis seperti yang diajarkan Ibnu Khaldun lebih dari 600 tahun lalu. Sebab, seperti kata beliau, “Negara yang adil akan terus hidup, meski tidak beragama. Tapi negara yang zalim akan runtuh, meski mengaku agamis.” *
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 19/12/2024
Penulis adalah Pendiri Republika Online 1995



