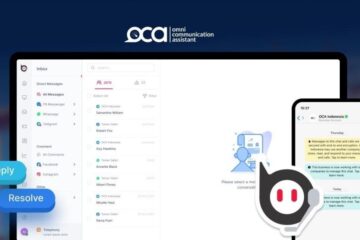J5NEWSROOM.COM, “Sekolah Bisa memiliki satu kelas yang hanya diisi maksimal 8 murid, sehingga sangat eksklusif dalam proses belajar. Di dalam ruangan yang sama, guru mengajarkan tidak lebih dari 8 murid.” Ujar Irwan Nurhadi, koordinator Sekolah Bisa di Bintaro, Tangerang Selatan.
Turmudi, yang lulus dari sekolah tersebut pada 2013, menambahkan, “Perhatian kepada murid sangat terdistribusi dengan baik.”
Sementara itu, Moh. Djodi Hardi Prajuri, yang kini menjabat sebagai tenaga ahli pendidikan di Kemenko Marves, menyatakan, “Kita fokus pada anak, karena mereka lebih aktif dalam kelas kecil.”
Pernyataan mereka menggambarkan sebagian karakteristik microschool, yang dijelaskan oleh kelompok advokasi AS National Microschooling Center.
Sekolah ini memiliki rata-rata 16 murid, memungkinkan guru lebih mengenal siswa mereka. Berdasarkan catatan kelompok tersebut, terdapat sekitar 1,5 juta murid di 95 ribu microschool di AS.
Microschool ini memiliki berbagai bentuk dan operasi. Beberapa di antaranya berdiri sebagai sekolah swasta, terakreditasi atau tidak, serta pusat kegiatan belajar yang mengikuti aturan homeschooling, didirikan oleh guru atau sekelompok orang tua dengan beragam model pendanaan.
Microschool di Indonesia
Saat ini, tidak ada data mengenai jumlah microschool atau muridnya di Indonesia. Irwan memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 100 sekolah di Jabodetabek. Sekolah Bisa adalah salah satunya.
Sekolah Bisa berawal dari proyek sosial siswa kelas 13 British School Jakarta. Pada 2009, mereka mengunjungi kampung Bulakan, daerah pemulung, dan menemukan banyak anak SD yang tidak bersekolah, hidup sebagai pengamen, silverman, pemulung, dan sebagainya.
Pada 2011, British School Jakarta bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia mendirikan Sekolah Bisa yang menyediakan pendidikan untuk anak-anak tersebut. Sejak delapan tahun lalu, sekolah ini dikelola oleh Yayasan Tangan Bagi Sesama, jelas Irwan.
Pandemi 2020 menginspirasi Djodi dan rekan-rekannya untuk mendirikan microschool di Depok. Djodi, yang ingin mendalami pendidikan, meninggalkan pekerjaan korporatnya untuk menjadi guru SD. Atas permintaan murid dan orang tua mereka, ia mendirikan Bright Microschool.
Informasi mengenai microschool di Indonesia yang minim membuatnya membaca lebih banyak tentang hal tersebut. Banyak orang yang ia tanyai baru pertama kali mendengar istilah microschool. Ia juga menemukan bahwa regulasi untuk sekolah jenis ini belum ada, sehingga meskipun Bright adalah program belajar after school, ia menganggapnya sebagai microschool yang mengadopsi konsep Amerika.
“Model ini sangat cocok saat pandemi karena pembelajaran dilakukan dalam grup kecil, mengurangi paparan COVID-19. Namun, anak-anak tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi,” ungkap Djodi.
Dana Operasional
Menurut catatan National Microschooling Center, microschool di AS memperoleh dana dari berbagai sumber, termasuk dana pemerintah. Banyak yang memungut biaya dari orang tua, dengan 43% memungut $5.000-$10.000 per tahun, dan 30% di bawah $5.000.
Irwan menyatakan bahwa banyak microschool di Indonesia, khususnya di Tangerang Selatan, yang tidak memungut biaya pendidikan karena pengelolanya mendedikasikan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan.
Sekolah Bisa, yang memiliki lima guru dan empat sukarelawan pengajar dengan kapasitas maksimal 25 murid, sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan, termasuk seragam, antar-jemput, serta sarapan dan makan siang. “Sumber dana operasional berasal dari donatur, baik individu maupun perusahaan,” jelas Irwan.
Sementara itu, Bright Microschool memungut biaya per jam yang disesuaikan dengan kondisi murid, dengan pertemuan dua hingga tiga kali per minggu selama dua hingga tiga jam.
Kurikulum
Djodi menjelaskan bahwa murid-muridnya tidak hanya belajar sesuai kurikulum sekolah. “Kita memiliki kurikulum yang dirancang sendiri dengan nilai-nilai yang diajarkan, namun juga memberikan pelajaran sesuai sekolah untuk memenuhi harapan orang tua agar anaknya berprestasi.”
Di sisi lain, Sekolah Bisa menggunakan kurikulum nasional untuk mempersiapkan murid berkompetisi di tingkat pendidikan selanjutnya. “Kurikulum kami harus setara,” tegasnya.
Sekolah ini juga mengombinasikan kurikulum tersebut dengan kurikulum hijau, sehingga murid-murid diharapkan menjadi insan yang ramah lingkungan, mencintai alam, serta memiliki sikap saling menghormati dan toleransi.
Tak Kalah Prestasi
Irwan menambahkan bahwa sebagai microschool, Sekolah Bisa mampu menghasilkan lulusan yang tidak kalah dari sekolah formal, termasuk negeri.
Salah satu alumni yang membanggakan adalah Turmudi. Semasa MTs, ia mengatakan, “Ranking saya tidak pernah jauh dari 5 besar. Kadang ranking 1, kadang 2, tapi jarang 3.”
Turmudi mengaku menikmati masa sekolah dengan jumlah murid 4-5 orang di kelasnya.
Saat membandingkan pengalamannya dengan pendidikan formal, ia mengungkapkan, “Keuntungannya, kami tidak perlu khawatir terhadap bullying yang mungkin terjadi di sekolah umum, mengingat latar belakang kami yang berbeda. Dengan jumlah siswa sedikit, kami sudah saling mengenal, sehingga tidak perlu khawatir.”
Ia merasa tidak perlu menyembunyikan latar belakang hidupnya yang mirip dengan teman-temannya. Turmudi, yang berayah buruh bangunan dan ibu pengamen, sempat terpaksa berhenti dari sekolah formal karena masalah biaya. Dengan semangat mengubah nasib, ia belajar keras hingga berhasil masuk sekolah negeri dan lulus dari SMK jurusan akuntansi. Kini ia bekerja di sebuah perusahaan ritel Jepang.
Walaupun di Sekolah Bisa ia tidak merasakan fasilitas sekolah besar, ia tetap senang bersekolah di sana. “Karena pilihan kami bukan soal lokasi, tapi keinginan untuk bersekolah,” katanya.
Orientasi pada Murid
Djodi menekankan bahwa di kelas kecil, murid merasa aman dan nyaman secara psikologis. “Mereka lebih leluasa menyampaikan pendapat dan unek-unek, jadi hubungan antar murid menjadi lebih dekat,” jelasnya.
Irwan setuju dengan Djodi mengenai pendekatan pembelajaran di sekolahnya. “Pendekatan ini sangat personal, terutama bagi anak-anak kami yang memiliki keunikan sendiri,” jelasnya. Pendekatan yang memungkinkan murid untuk berbagi tentang keluarga atau masalah membuat mereka lebih bahagia di sekolah.
Tantangan
Berdasarkan pengalaman Djodi, ia menghadapi dua tantangan dalam mengelola microschool. Dari sisi operasional dan akademik, meski birokrasi tidak terlalu banyak, tantangan dari sisi bisnis adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep microschool. “Apakah orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah dengan murid sedikit?” tanyanya, yang akhirnya menutup microschool-nya setelah menyelesaikan program S-2 karena kesibukan kerja.
Djodi berpendapat bahwa microschool memiliki prospek baik dan bisa menjadi masa depan pendidikan, didukung oleh tiga faktor: individualisme yang meningkat, kemungkinan adanya gelombang pandemi lainnya, dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan.
Irwan juga menyadari pentingnya pengelolaan dana agar sekolahnya tetap beroperasi. Ia mengungkapkan bahwa kesulitan dalam mencari murid yang dialaminya di tiga tahun pertama tidak lagi menjadi masalah. Ia yakin masih banyak anak-anak yang membutuhkan pendidikan di Jakarta. “Banyak anak yang sangat memerlukan bantuan pendidikan,” tutupnya.
Sumber: voaindonesia.com
Editor: Saibansah