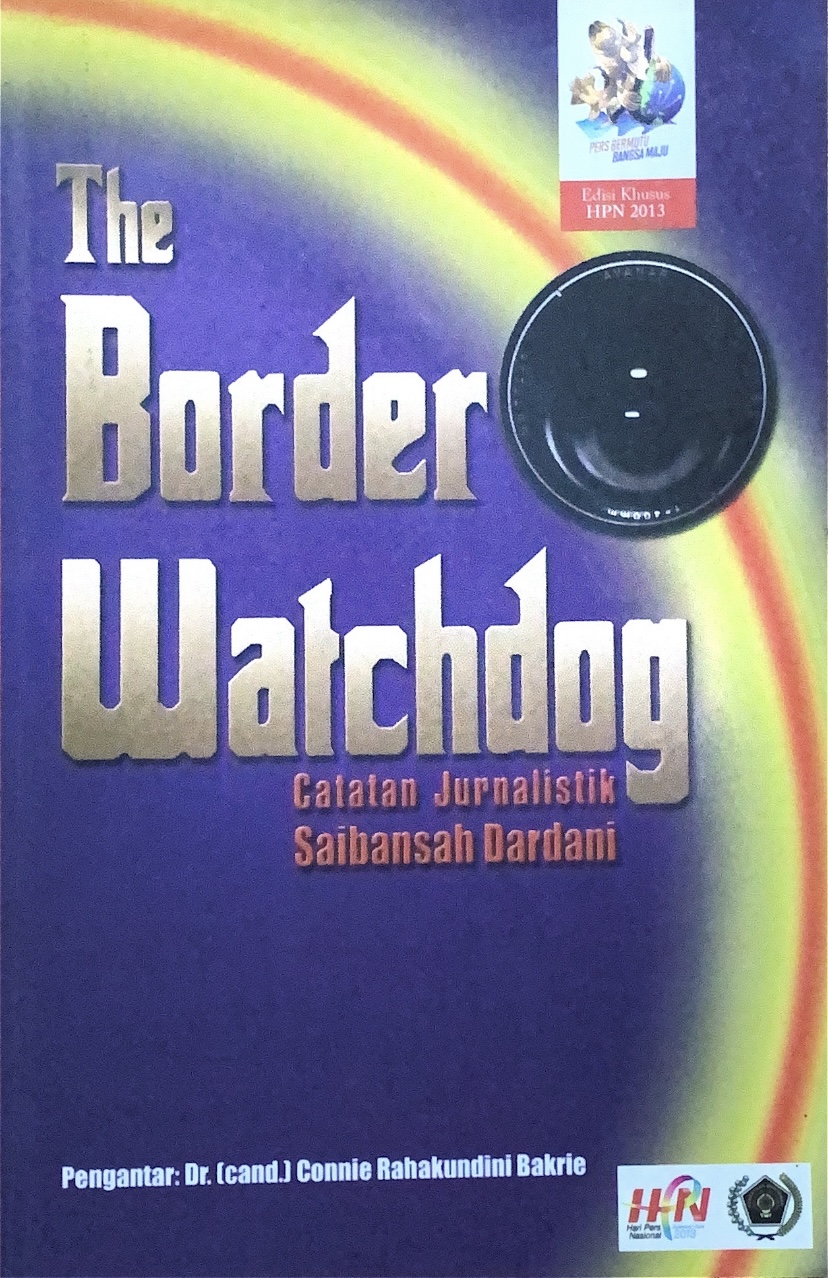
MENGKRITISI NASIONALISME MASYARAKAT PERBATASAN
APAKAH karena saling berniaga, maka nasionalisme masyarakat perbatasan diragukan? Pertanyaan itu muncul pada sesi diskusi Dialog Pemuda II bertajuk “Identitas Kebudayaan Indonesia di Perbatasan” di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, 20 Mei 2011 lalu. Sebagai salah seorang pembicara dalam forum itu, pertanyaan ini sangat menggelitik pikiran saya. Karena sudah lumrah bahkan sudah terjadi sejak lama, bahwa masyarakat perbatasan tidak pernah ada sekat antara dirinya dengan warga negara tetangga. Masyarakat Pulau Batam, sejak dulu sudah terbiasa berniaga dengan masyarakat Singapura. Ketika itu mereka tidak perlu membawa paspor untuk sekadar berniaga dan berbarter barang dagangan. Karena masyarakat dari kedua negara saling membutuhkan dan mereka hidup damai berdampingan. Lalu, apakah karena itu kadar nasionalisme mereka patut dipertanyakan?
Sebaliknya, apakah masyarakat ibukota atau mereka yang biasa hidup hedonis di kota-kota besar, mereka lebih nasionalis? Jika ukurannya adalah gaya hidup dan keperbihakan mereka pada produk dalam negeri, separtinya justru masyarakat ibukota atau pun mereka yang hidup di perkotaan yang patut dipertanyakan nasionalismenya? Bagaimanan tidak, untuk sekadar menyeruput kopi saja, mereka sudah menghamburkan uang untuk disedot ke luar negeri. Ya, ngopi di Sturbuck atau kedai kopi sejenisnya. Atau, untuk memperbaiki penampilan diri, maka baju, calana, tas sampai dengan dompet dan “perangkat daleman” mereka pun bukan buatan anak negeri. Demi merek, mereka rela menggelontorkan uang untuk disedot keluar negeri.
Sementara masyarakat perbatasan, mereka memang menggunakan produk-produk luar. Karena memang itulah sumber satu-satunya produk yang mereka pergunakan sehari-hari. Saling barter antara sesama masyarakat perbatasan adalah lumrah dan sudah terjadi sejak lama sekali. Jadi, mereka menggunakan produk luar bukan demi gengsi atau penampilan diri. Tapi memang terjadi barter kebutuhan barang diantara mereka.
Kini, setelah hukum dan aturan menjerat dan mensekat-sekat mereka, maka semuanya menjadi berbeda. Tidak bisa lagi, masyarakat Pulau Batam membawa kayu arang dan ikan bilis kering ke Singapura tanpa paspor untuk pulang membawa barang sekarung gula dan beberapa peralatan elektronik ala kadarnya. Begitu pula halnya dengan masyarakat lain di seluruh wilayah perbatasan di Indonesia. Kondisi ini sudah pasti membuat mereka harus menyesuaikan diri. Beras dari negeri Siam pun tak bisa lagi mereka bawa dari Singapura bersama gula dan kebutuhan lainnya, seperti dulu. Semuanya harus distop demi hukum dan aturan kepabeanan masing-masing negara.
Sialnya, setelah mereka tidak bisa lagi mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari itu dari negeri tetangga, pasokan dari dalam negeri pun tersendat-sendat. Kalau pun ada, harganya sudah gila. Kondisi ini terjadi di sejumlah daerah perbatasan di Indonesia. Bayangkan, untuk mendapatkan satu sak semen, saudara kita di perbatasan di Nunukan Kalimantan Timur harus membayar hingga ratusan ribu rupiah, bahkan pernah menyentuh harga satu juta rupiah per sak. Kondisi ini juga berlaku untuk komoditi lainnya, seperti gula dan beras.
Seperti diungkapkan seorang pembicara dalam forum diskusi Dialog Pemuda II asal Nunukan, Rahman. Dia mengungkapkan, betapa tidak terbangunnya Nunukan. Bahkan, pemasangan listrik sudah berhenti sejak 2001. Infrastruktur yang rusak pun turut menggoyang tatanan ekonomi, segala sesuatu menjadi amat mahal. Ia mencontohkan ongkos ojek dari pos batas sampai Krayan mencapai Rp 200 ribu sekali jalan. Dan jika hujan, harga premium melambung menjadi Rp 50 ribu per liter. Di lain hal, harga semen di Krayan bisa mencapai Rp. 1 juta per sak.
Ambruknya kehidupan sosial-ekonomi di Nunukan bukanlah diakibatkan oleh adanya perang, melainkan dikarenakan ketiadaan pembangunan. Dan ini membuat banyak warganya hengkang, memilih untuk menjadi warga negara Malaysia ketimbang warga negara Indonesia. “Paman saya sendiri pindah ke Malaysia sudah 30 tahun. Alasannya, kalau pindah warga negara maka anaknya mendapat jaminan sekolah,” tutur Rahman.
Kondisi tak berpembangunan juga dialami kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, seperti Entikong, Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Seperti Nunukan, di Entikong juga terjadi perpindahan warga negara secara berangsur-angsur. Sebetulnya, seluruh petinggi negara sudah berdatangan ke Entikong. Hanya saja, kondisi tetap tak berubah. Tak ada kemajuan di daerah ini. “Rasanya cuma malaikatlah yang belum pernah mampir ke Entikong,” ungkap pemakalah lain, Hendrikus Adam dari Kalimantan Barat.
Jadi, sesungguhnya problem utama masyarakat di perbatasan bukanlah soal nasionalisme. Tapi soal perut. Kebutuhan mendasar untuk tetap hidup, itulah yang membuat mereka harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Maka, alangkah kejinya mereka yang mempertanyakan nasionalisme masyarakat perbatasan itu. Begitu pula halnya penguasa yang membiarkan mereka hidup dalam serba keterbatasan. Lalu melarang mereka untuk berniaga dengan masyarakat negara tetangga. *
24




